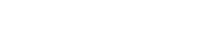Buku yang diterbitkan jarang terjual, apalagi mencetak keuntungan. Tidak ada ekosistem yang menopang dunia sastra. Semua serba-relawan, serba-sukarela, hingga akhirnya serba-diabaikan.
BACA JUGA:LELANANGE JAGAD MERINGKUK DI KOSAN
BACA JUGA:Wanita yang Nglungsungi Seperti Ular
Saya bahkan pernah menawarkan kepada siswa untuk ikut membaca puisi di sebuah acara, dan yang terjadi adalah penolakan kolektif.
“Gratis, Pak?” tanya mereka, seperti menegaskan bahwa sastra bukan hanya tak berharga, tetapi juga tak relevan dengan apa yang mereka cari.
Kegelisahan ini semakin pekat ketika saya melihat ironi di balik meja-meja birokrasi. Ada pejabat dinas yang semestinya menjadi pelindung kebudayaan, tetapi justru memperkaya diri melalui kegiatan fiktif.
Stempel palsu menjadi alat legitimasi untuk menguras anggaran yang sebenarnya bisa digunakan untuk membangun ekosistem seni yang sehat.
BACA JUGA:DI NEGERI PARA PESOLEK
BACA JUGA:Sebelum Pandemi dan Sesudah Itu Mati
Bagaimana sastra bisa bersaing dengan dunia lain yang memiliki struktur dan penghargaan yang jelas, jika yang terjadi adalah pengkhianatan oleh pihak yang seharusnya berperan sebagai penjaga?
Dunia telah berubah. Anak muda kini tidak lagi mau bergerak hanya demi nama besar atau kebanggaan kosong. Mereka mengejar sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa menjadi modal finansial bagi masa depan mereka.
Kursus keterampilan praktis seperti setir mobil, masuk agensi TKI, atau baby sitter lebih diminati karena memberi jaminan pekerjaan.
Di sisi lain, sastra menawarkan apa? Sebuah nilai abstrak yang bahkan tidak dianggap cukup penting oleh penyelenggara acara untuk memberikan sertifikat apresiasi.
BACA JUGA:PEREMPUAN YANG MENJUAL DIRINYA PADA JARAK
BACA JUGA:Anak Sekolah Dasar yang Mati Tak Berdasar
Saya pernah meminta panitia acara sastra membuatkan sertifikat PDF bagi para peserta, tetapi jawaban yang saya dapat hanyalah seribu alasan penolakan. Bagaimana sastra bisa berdiri sejajar dengan bidang seni lainnya jika penghargaan sekecil itu pun tidak diberikan?