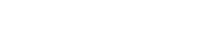Jejak Cinta

Malik Ibnu Zaman-istimewa-
Karya Malik Ibnu Zaman
Jam menunjukkan pukul tujuh pagi. Aku baru saja selesai menghitung pemasukan kafe tadi malam. Karyawan-karyawanku sudah pulang setelah Subuh, menyisakan aku sendirian di kafe ini.
Bangunannya tidak jauh dari rumahku, hanya sepelemparan batu. Kafe ini terdiri dari tiga lantai, dengan lantai ketiga berfungsi sebagai perpustakaan kecil yang kubuka untuk umum.
Membangun kafe ini bukan perkara mudah. Lima tahun penuh perjuangan aku lalui untuk menabung dan mengumpulkan modal, menjalani pekerjaan demi pekerjaan, kebanyakan terkait tulis-menulis.
Maka, ketika aku memutuskan meninggalkan kota besar untuk menetap di kampung, banyak teman yang menganggapku gila.
BACA JUGA:MALING KONDANG
BACA JUGA:Mendoakan Kematian?
Saat itu, karierku sedang berada di puncak. Aku sudah menjadi redaktur di salah satu media ternama, baru saja memenangkan sayembara sastra nasional. Namun, bagiku, mimpi membangun kampung halaman lebih penting daripada gemerlap kota.
“Kamu yakin mau meninggalkan semuanya?” tanya Zaldi, sahabatku, saat aku mengutarakan rencana itu.
“Ini mimpiku, Zal. Aku ingin kampung halaman menjadi tempat yang lebih baik. Tidak hanya tempat untuk menikmati masa tua, apalagi sekadar tempat dimakamkan,” jawabku yakin.
Zaldi tertawa sambil menepuk bahuku. “Tapi siap-siap saja. Kampung itu nggak pernah kehabisan bahan gosip. Termasuk soal kejombloanmu,” ujarnya sambil mengedip.
“Sialan,” jawabku sekenanya. Meski kesal, aku tahu dia ada benarnya.
BACA JUGA:Tirani Biru dan Isinya yang Terbelenggu
BACA JUGA:Dendam Seorang Perempuan
Setahun menetap di kampung, kejombloanku memang jadi bahan gunjingan. Namun, aku tak terlalu peduli. Aku melihat pamanku yang memilih tetap melajang hingga usia senja.