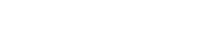Lukisan Merah

Ilustrasi-radarutara.bacakoran.co-
“Saya ingin bertanya sesuatu..” katanya pada perempuan tua yang merepet tentang sarapan dan keran air yang kadang macet. Sekali lagi ia kembali ke lorong dengan lukisan yang sama, kali ini ada tetesan darah di salah satu gambar. Seorang lelaki tinggi berdiri di belakangnya, suaranya dingin ketika bertanya, “Kenapa kau kesini?”
“Hanya pergi,” jawab Seroja, ambigu. Ia menghela napas panjang. “Kembalilah, ibu memintamu pulang,” pinta Seroja, muak pada sikap yang tak pantas disebut kakak.
Lelaki itu tertawa getir. “Pergi? Kau pikir hidup ini cuma soal keluar‑masuk sesuka hatimu?”
Seroja menoleh tajam. “Lalu menurutmu apa? Tinggal di sini, pura‑pura baik‑baik saja?”
“Kau itu cuma kabur. Kalau ada masalah, kau pergi. Kalau disuruh orang, kau lari.” Nada kakaknya merendah, seperti biasa.
Seroja mengepal tangan. “Aku pergi karena kalian semua membuatku gila.”
“Kami?” Lelaki itu mendekat, suaranya meninggi. “Kau bahkan tidak layak disebut bagian dari keluarga. Kau—”
“Cukup!” Seroja memotong, matanya bergetar menahan emosi. “Kau bicara seolah kau malaikat padahal kau tidak pernah melakukan apa pun selain merusakku.”
BACA JUGA:'Alana: A Journey to Love', Novel Karya Mahasiswa Bengkulu
BACA JUGA:Kami Tunggu Ibu di Api
Kakaknya mencibir, menuduh, menuduh lagi. Seroja hampir berteriak: “Kau tidak pernah ada ketika aku dihancurkan oleh orang‑orang yang kau biarkan masuk hidup kita. Kau cuma pandai menghakimi dari jauh.”
Pertengkaran itu menajamkan luka lama. Seroja menolak label adik yang dipaksakan; ia menolak menjadi bagian dari sandiwara keluarga yang meremukkan. Ia melangkah pergi, meninggalkan kata‑kata yang menggantung tajam di udara.
“Sudah lebih dari cukup. Aku akan pulang,” gumamnya pada dirinya sendiri, langkahnya menuju stasiun. Ia akan kembali ke negeri asalnya, cukup lelah untuk terus bertahan di negeri orang. Makian kakaknya masih terdengar, namun lebih baik mendengar itu daripada terus tinggal di tempat yang mengikisnya.
Kembali rumah, Seroja mendorong sosok yang ia panggil Oma ke sofa. Suara kesakitan menggema, Oma menghantamkan kepala ke dinding, darah bercecer. Kali ini Seroja tidak menolong. Ia mendengar bisikan “Dasar anak sinting… biarkan aku membunuhmu…” Ia hanya akan kembali melukis dengan sentuhan tangan yang setiap harinya bekerja keras dengan harapan mungkin Tuhan akan berbaik hati padanya atau mungkin kakak yang berbaik hati.
Di penginapan, lukisannya tergantung yaitu karya kecil dengan paduan warna kelam. Pengunjung melihat, mungkin hanya melihat noda dan sapuan warna. Bagi Seroja, setiap goresan adalah jejak langkahnya. Setiap malam yang ditinggalkan, pintu yang tak terbuka, kata‑kata yang melukai, dan keputusan untuk pergi. Ia adalah anak kecil yang dipaksa hidup sendiri, namun dari kesendirian itu lahir bahasa warna yang tak bisa dibungkam.