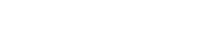"Barangkali kamu suruh datang ke makamnya, kamu sudah lama sekali nggak pulang kampung," kata ibu.
"Sudah yah bu, aku mau berangkat kerja dulu. Nanti aku akan ambil cuti dari kantor."
BACA JUGA:Perempuan Penggenggam Pasir
BACA JUGA:Sungai Yang Meminta Kedatangan
Sehari-hari aku bekerja menjadi jurnalis di sebuah media yang terletak di Jakarta Pusat. Jurnalis memang tak tentu kerjanya, hari itu aku berangkat siang, setelah Dzuhur.
Media tempatku bekerja unik, berbeda dari kebanyakan media pada umumnya. Keunikan tersebut mungkin karena faktor terafiliasi dengan organisasi keagamaan.
Hampir 90 persen krunya diisi oleh anak kiai, ada anak kiai dari Cirebon, Brebes, Semarang, Magelang, Bekasi. Hal inilah yang membuat temanku yang bekerja di media mainstream keheranan.
"Kok kamu bisa masuk ke media tersebut, kamu ini kan bukan anak kiai, bukan santri pula," ujar Icus suatu ketika.
BACA JUGA:Rubik Hati Naras
BACA JUGA:SESUATU DALAM MAHKOTANYA
"Jangan salah, meskipun gua bukan anak kiai. Begini-begini gua ini pernah nyantri selama tiga tahun, meskipun di pondok gua lebih banyak tidur sih."
"Tetapi nyaman kan di sana? Gaji aman?" tanya Icus nyerocos sambil makan.
"Ya begitulah," ujarku tertawa.
"Gajinya ya gaji khidmat," imbuhku.
Ya, memang sebagian orang di sana tidak suka terhadap diriku. Beberapa kali aku dicari kesalahannya. Kesalahan yang terkesan diada-adakan. Namun, lagi-lagi aku masih aman. Tetapi siang itu lain, aku dipanggil oleh Pimred, Laniv namanya. Aku dipecat. Masih mending dipecat kalau dapat pesangon. Lah ini boro-boro dapat pesangon, gaji hanya dibayarkan separuh. Tetapi aku tidak bisa protes, sebab memang tidak ada hitam di atas putih.
BACA JUGA:Celurit Matrah