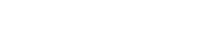Wajah “Damai” Islam Asia Tenggara

Ilustrasi. Foto: Ist--
Asia adalah rumah bagi 65 persen pemeluk Muslim di dunia, dan Indonesia, di Asia Tenggara, adalah negara dengan pemeluk Muslim terbesar di dunia.
Menariknya, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang mempunyai sikap sosial dan kepercayaan yang sangat beragam. Secara sosial budaya penduduk di kawasan ini mayoritas memeluk Islam, tetapi pada kenyataan realitas sosial, budaya, dan keyakinan yang berkembang di dalamnya menunjukkan heterogenitas yang berbeda dengan warna keislaman di Timur Tengah.
Sayangnya bicara tentang kajian Islam di kawasan Asia Tenggara, bisa dikata cukup terlambat dibandingkan kajian kawasan Islam di Timur Tengah. Ini mudah dipahami, mengingat selama ini identifikasi terhadap Dunia Islam tampaknya lebih lekat dan sebatas direduksi pada corak rupa sosiokultural di Timur Tengah.
Namun belakangan tampaknya kajian Islam Asia Tenggara mulai menggeliat kuat dan posisi populasi Islam di kawasan itu juga mulai diperhitungkan. Hal ini tentu saja tidak terlepas karena kuantitas pemeluk Islam jumlahnya sangatlah besar. Hampir di seluruh negara yang ada di Asia Tenggara, penduduknya baik dalam jumlah mayoritas ataupun minoritas, bisa dipastikan memeluk agama ini.
Sebutlah misalnya Islam menjadi agama resmi di negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya sekitar 90 persen menganut agama Islam. Sementara itu pemeluk Islam yang terdapat di Birma atau Myanmar, juga sebagian kecil wilayah Filipina yaitu Mindanau, pun juga dipeluk di Muangthai, Kamboja, dan Singapura, Islam nisbi hadir sebagai kelompok agama minoritas.
BACA JUGA:Kelenteng Bersejarah di Pulau Seribu Masjid
Seperti telah diulas dalam artikel sebelumnya, Sejarah Mendunia Islam, maka bicara istilah Islam Asia Tenggara (Southeast Asian Islam) sendiri sering digunakan secara bergantian dengan istilah 'Islam Melayu-Indonesia' (Malay-Indonesian Islam). Dalam konteks kajian Islam inilah, Moeflich Hasbullah (2017) dalam karyanya Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara mencatat munculnya gejala perubahan arah mata angin pandangan masyarakat Barat terhadap posisi Dunia Islam, yaitu dari kawasan Timur Tengah ke di Asia Tenggara. Di sini Hasbullah memaparkan beberapa fakta menarik.
Majalah TIME, edisi 23 September 1996, meluncurkan sebuah tulisan utama berisi reportase khusus tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Judulnya cukup sensasional “The New Face of Islam”. TIME melukisan masyarakat AsiaTenggara sebagai “tengah menatap pembentukan sejarahnya” (seeing history in the making). “Masyarakat Asia Tenggara,” lanjut tulis TIME, “mulai merasakan identitas Islam mereka yang lebih lembut, dibentuk oleh angin tropis dan pengalaman multikultural yang panjang, tampak sedang menerangi jalan menuju sebuah masa depan Islam yang besar.”
Dalam pandangan yang relatif sama, majalah Asiaweek, edisi 4 April 1997, juga menurunkan artikel John L Esposito berjudul Islam Southeast Asia Shift, A successthat could lead renewal in the Muslim world. Dalam artikel itu, Esposito melukiskan pengalaman dan keterkejutannya melihat wajah Islam kontemporer di Asia Tenggara. Apa pasalnya?
Menurut Esposito, lebih dari dua puluh tahun yang lalu, ia pernah berkata kepada kolega kuliahnya, bahwa ia sama sekali tidak tertarik kepada kajian Islam di Asia Tenggara. Ketika itu banyak pengamat Islam yang mengidentikkan Islam dengan Arab atau Timur Tengah semata, ujar Esposito. Posisi Islam di Asia Tenggara juga dianggap bernilai sebagai Islam pinggiran. Namun, apa yang ia katakan kemudian di tahun 1990-an? Ternyata Esposito menyimpan banyak kekaguman.
“Pada awal abad ke-21, hal itu berubah secara dramatis. Globalisasi ekonomi, kemunculan Asia sebagai pasar yang kuat dan komunikasi massa telah memicu “penemuan kembali” Islam Asia Tenggara”, baik ekonomi maupun budaya. Lama dibayangi oleh kepentingan strategis minyak Arab dan politik eksplosif Asia Barat, Malaysia dan Indonesia muncul untuk memainkan peran kepemimpinan di dunia Muslim” ujar Esposito.
Jauh sebelum TIME dan Asiaweek mengulas variasi keislaman di Asia Tenggara, Mohammed Ayoob (1981) dalam The Politics of Islamic Resurgence telah mengkritisi pandangan masyarakat akademis Barat yang cenderung monolitik terkait kajian Islam. Menurut Ayoob, pandangan monolitik ini cenderung mengeliminasi atau mengabaikan adanya konteks divergensi baik sosial, ekonomi, dan politik di antara kawasan-kawasan Islam yang demikian luas dan menutup mata terhadap variasi dan keragaman kultural di banyak negara Islam lain di luar Timur Tengah.
Kembalinya Islam rahmatan lil 'alamin
Pertanyaannya ialah, mengapa kita harus mengalihkan perhatian pada kawasan AsiaTenggara? Apakah nilai pentingnya wilayah ini bagi peradaban Islam? Bukankah Asia Tenggara adalah sebuah kawasan “Islam pinggiran” yang jauh dari “pusat” Islam di Timur Tengah, sehingga implikasinya warna keislamannya tentu jauh dari ortodoksi kitab suci alias cenderung sinkretis?
Walaupun pelbagai pertanyaan di atas mungkin secara relatif adalah benar, pertanyaan tersebut sesungguhnya justru merepresentasikan asumsi umum, bahwa bagi banyak orang, Islam masih diidentikkan dengan Timur Tengah. Pandangan ini, pada gilirannya, pasti mengabaikan multiwajah, luasnya wilayah, batas teritorial, dan heterogenitas kebudayaan di Dunia Islam secara luas. Selain itu, pelbagai pertanyaan itu juga mengabaikan aspek penting dari perkembangan Islam kontemporer di kawasan Asia Tenggara itu sendiri.
BACA JUGA: Kembalinya Saksi Bisu Sejarah Nusantara
Ya, bicara Islam Asia Tenggara, Esposito telah menggarisbawahi posisi Indonesia dan Malaysia sebagai saripati terpentingnya. Melihat karakteristik Islam di Indonesia, juga di Malaysia, Esposito melihat potensi kedua negara ini cukuplah menjanjikan dan mungkin muncul sebagai alternatif bagi kebangkitan Dunia Islam.
Pasca-Perang Dingin di 1990-an, saat Islam karena propaganda Barat kemudian diidentikan dengan radikalisme dan dianggap tidak cocok dengan modernisasi serta demokrasi, seturut Esposito—berbeda warna secara kontras dengan Islam di Asia Barat—menurutnya Islam di Asia Tenggara “is far more multireligious and multicultural and projects a more moderate and pluralistic profile.”
Lebih jauh menjawab thesis Samuel Hutington terkait “benturan peradaban”, menurut Esposito, jika banyak orang mempertanyakan apakah Islam dan modernisasi bisa bertemu dan memperingatkan tentang akan munculnya benturan antarperadaban antara Islam dan Barat, maka baginya “Malaysia telah membuktikan salah kaprahnya stereotip-stereotip sederhana semacam itu.”
Akar kehidupan keislaman secara moderat dan berprofil pluralistik di Asia Tenggara tentu memiliki akar sejarah yang panjang. Seperti telah diulas dalam artikel terdahulu yaitu Sejarah Mendunia Islam, seorang Islamolog bernama Thomas W Arnold dalam buku klasiknya The Preaching of Islam menyimpulkan, bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai.
Pun Azyumardi Azra tiba pada kesimpulan yang sama. Dalam Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan, Azra mengatakan Islam Asia Tenggara berbeda dari Islam Timur Tengah. Islam di Asia Tenggara bersifat lebih lunak, ramah, jinak, dan toleran, atau bahkan sangat akomodatif terhadap kepercayaan, praktek keagamaan, tradisi dan budaya lokal. Sikap akomodatif ini, yang oleh tradisi pesantren di Jawa disebut sebagai pendekatan tasamuh, tawazun, dan tawasuth, telah memberikan “ruang dialog” bagi semua komunitas yang ada saat itu untuk mencerna keberadaan Islam sebagai agama baru di Nusantara.
Juga kesaksian etnografis seorang antropolog bernama Clifford Geertz. Dalam karyanya Negara, The Theater State in Nineteenth-Century Bali, Geertz (1971) secara implisit mengatakan Indonesia merupakan miniatur dunia, di mana hampir semua kebudayaan dan agama-agama dunia dapat hidup harmonis bersama-sama dan berkembang secara ko-eksistensi damai selama berabad-abad.
“Semua aliran budaya yang, selama tiga ribu tahun, telah mengalir, satu demi satu, ke Nusantara—dari India, dari China, dari Timur Tengah, atau bahkan dari Eropa—menemukan representasi kontemporer mereka di beberapa tempat: di Hindu Bali; di China Town di Jakarta, Semarang, atau Surabaya; juga di wilayah-wilayah Muslim yang kuat seperti di Aceh, Makassar, atau Bukit Tinggi Padang; di wilayah-wilayah Kristen di Minahasa dan Ambon, atau Flores yang beragama Katolik dan Timor,” ujar Geertz.
Ya, mudah ditebak, sikap moderat dan profil pluralistik serta semangat akomodatif dari Islam Asia Tenggara ini sudah pasti tidak terlepas dari warna sufisme dan tasawuf yang mewarnai penyebaran Islam di masa lalu. Pijakan sufisme atau tasawuf ini memungkinkan nilai-nilai Islam hadir dan bergerak dalam aras substansi ketimbang sekadar mengorientasikan pada pelembagaan azas-azas legalitas formal keagamaan seperti implementasi hukum Syariah.
Sialnya, sebelum momentum kebangkitan Islam Asia Tenggara terjadi, terjadilah tragedi Peristiwa 11 September 2001 atau 9/11, dan pascakejadian tersebut membawa implikasi menguatnya pandangan stereotip bukan semata di lingkungan akademis melainkan juga dalam atmosfir common sense masyarakat Barat.
Sialnya lagi, menurut Esposito (2010) dalam The Future of Islam juga mencatat sejarah Islam belakangan memang justru memperlihatkan wajah yang tak menggembirakan. Di sana-sini muncul gejala peningkatan kekerasan. Kekerasan ini bahkan terjadi antarpemeluk Islam sendiri, yang ditandai oleh pelarangan terhadap aliran tertentu karena dianggap sesat atau menyimpang. Esposito mengambil contoh Malaysia melarang aliran Syiah dan Indonesia melarang Ahmadiyah.
Ya, pengalaman akan kehidupan multiagama dan multibudaya di masa lalu yang harmonis dan damai, juga praktik keagamaan sekarang ini—meski belakangan muncul kekurangan di sana-sini—bagaimanapun adalah basis yang sangat berarti bagi masyarakat Asia Tenggara, terutama bagi Indonesia dan Malaysia.
BACA JUGA:Jejak Masa Lalu Sirih dan Pinang
Berpijak pada basis pengalaman historis di masa lalu inilah, penting bagi Indonesia untuk kembali belajar mengembangkan kehidupan yang demokratis dan berorientasi pada pengembangan kehidupan keagamaan secara inklusif dan tolerans. Sudah tentu adanya koreksi diri (self-criticism) secara sosial pun menjadi sangat penting untuk dikembangkan sebagai basis penguatan Islam “jalan tengah” ke muka.
Pada titik ini, penting diingat bahwa arus besar keagamaan di Indonesia kontemporer sebenarnya diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Nama besar NU dan Muhammadiyah telah menjadi merek paten bagi gerakan Islam moderat, modern, terbuka, dan inklusif, serta konstruktif. Moderasi dan toleransi menjadi karakteristik utama bagi kedua organisasi tersebut. Sederhananya, sikap moderat dan profil pluralistik keagamaan dari NU dan Muhammadiyah inilah yang telah mewarnai corak sosial dan budaya Islam di Indonesia selama ini.
Kendatipun tentu saja ada organisasi Islam yang radikal atau bersifat sektarianisme, dan belakangan sering memantik aksi kekerasaan dan sikap intoleransi, tetapi secara kuantitas jumlahnya jelas sangatlah kecil. Sehingga lebih jauh, kelompok kecil ini seharusnya tidak patut menempatkan diri seolah-olah sebagai kelompok arus utama dan sekaligus merepresentasikan wajah Islam di Indonesia.
Di sisi lain, NU dan Muhammadiyah sudah tentu haruslah segera bergegas untuk aktif memprakarsai penguatan kembali basis model tafsiran keagamaan yang telah dikembangkan kedua ormas itu selama ini.
Sumber : Indonesia.go.id