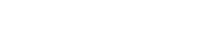Defisit Kebudayaan: Sastra dalam Bayangan Pasar dan Prinsip 5W-1H

Fileski Walidha Tanjung -Fileski Walidha Tanjung -
BACA JUGA:Anak Sekolah Dasar yang Mati Tak Berdasar
Saya pernah meminta panitia acara sastra membuatkan sertifikat PDF bagi para peserta, tetapi jawaban yang saya dapat hanyalah seribu alasan penolakan. Bagaimana sastra bisa berdiri sejajar dengan bidang seni lainnya jika penghargaan sekecil itu pun tidak diberikan?
Lebih menyedihkan lagi adalah mindset yang mengakar di banyak instansi: para pegiat sastra sudah cukup senang diberi ruang untuk tampil.
Sebuah anggapan yang, tanpa disadari, menjadi pisau tumpul yang perlahan-lahan membunuh regenerasi sastra. Anak muda kehilangan minat karena merasa tidak ada manfaat yang bisa diraih dari dunia ini.
Dan dengan hilangnya minat itu, sastra tak hanya kehilangan penulis-penulis potensial, tetapi juga kehilangan pembacanya, kehilangan audiensnya, kehilangan maknanya.
BACA JUGA:Kembali ke Laut
BACA JUGA:Ibu Sambung
Indonesia, dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa, telah mengalami berbagai transformasi budaya yang mencerminkan dinamika zaman.
Seiring berjalannya waktu, sastra—sebagai bentuk tertinggi dari kebudayaan yang berakar dalam kata—mendapatkan tempat yang semakin terpinggirkan.
Kegelisahan ini mencuat dalam pernyataan Prof. Djoko Saryono yang menggambarkan Indonesia sedang dilanda defisit kebudayaan. Di tengah arus globalisasi yang cenderung materialistis, sastra sebagai sarana eksplorasi diri dan peradaban mengalami krisis penghargaan.
Namun, di balik fenomena ini, terdapat makna yang lebih dalam tentang eksistensi sastra, baik dalam konteks filosofi, sosiologi, maupun estetika.
BACA JUGA:GUBUK KECIL DAN RINTIK HUJAN
BACA JUGA:Wanita yang Nglungsungi Seperti Ular
Melalui karya-karya besar sastra, baik yang klasik maupun kontemporer, kita dapat menggali kembali kedalaman nilai-nilai yang terkandung dalam sastra, yang pada dasarnya adalah cerminan peradaban manusia itu sendiri.
Secara filosofis, sastra memberikan sebuah ruang bagi manusia untuk menguji dan merefleksikan eksistensinya. Sebagaimana dikatakan oleh F. Scott Fitzgerald dalam The Great Gatsby, "Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us."